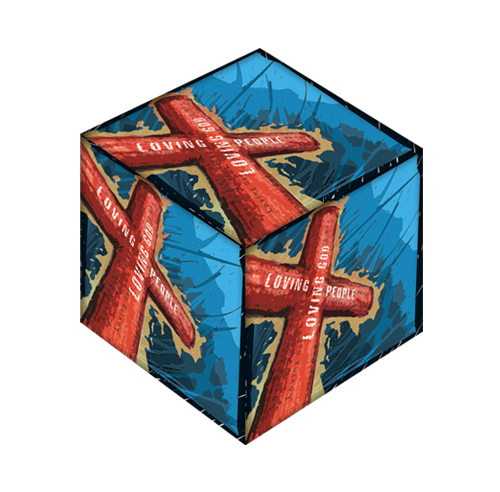-
Worship Service
07:00 - 16:30 WIB



Yohanes 19:38-40, "Sesudah itu Yusuf dari Arimatea --ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi-- meminta kepada Pilatus, supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira lima puluh kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat."
Ketika merenungkan penyaliban Tuhan Yesus, kita mungkin sering berhenti pada salib dan langsung melompat ke kebangkitan. Namun di antara dua peristiwa besar itu, ada satu sosok yang barangkali kerap luput dari perhatian kita, yaitu Yusuf dari Arimatea.
Yusuf dari Arimatea bukanlah tokoh utama dalam kisah Injil, ia hanya disebut satu kali dalam masing-masing Injil (Matius sampai Yohanes), tepat pada bagian penguburan Yesus. Namun dalam momen singkat itu, tersimpan keberanian dan pengorbanan yang sangat besar. Yusuf adalah anggota Sanhedrin—suatu majelis tertinggi Yahudi—yang memiliki kekayaan, kekuasaan, dan reputasi. Namun ketika Yesus wafat, Yusuf melakukan sesuatu yang mengejutkan, ia secara terbuka menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus dan meminta tubuh Yesus untuk dikuburkan di makam pribadinya (Yohanes 19:38).
Lukas menyebutnya sebagai "seorang yang baik lagi benar" (Lukas 23:50). Tetapi tindakannya bukan hanya soal kemurahan hati atau keberanian. Dalam suatu referensi, dikatakan bahwa dengan menguburkan tubuh Yesus, Yusuf juga mengubur masa lalunya. Ia memilih jalan yang akan memisahkannya dari sistem keagamaan yang telah menolak Mesias. Ia memilih untuk hidup dalam pemisahan moral, menjadi saksi yang menentang ketidakbenaran bangsanya sendiri.
Bayangkan, keberanian yang dibutuhkan untuk melakukan hal itu. Saat para murid-Nya tersebar ketakutan, melarikan diri, Yusuf dari Arimatea melangkah maju. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada jaminan kebangkitan di depan matanya. Namun, ia tetap memilih untuk berdiri di sisi Yesus—Tuhan yang telah disalib.
Pertanyaannya, apakah kita memiliki hati seperti Yusuf? Bersediakan kita berdiri bagi Kristus, bahkan ketika itu mungkin saja mengorbankan kenyamanan, reputasi, ataupun bahkan hubungan kita? Apakah kita rela kehilangan segalanya demi memperoleh Kristus? Apakah Ia masih yang terutama, lebih daripada segala-galanya dalam hidup kita, ataukah kini sebaliknya segala sesuatu yang menjadi lebih daripada Dia?
~ FG
- TERKEPUNG
- 24 April 2025
- Yesaya 40:31, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, ... Lihat Selengkapnya
- MENARI DALAM BADAI
- 23 April 2025
- Setiap "badai" adalah suatu sekolah, setiap ujian adalah guru, setiap pengalaman adalah didikan, setiap kesukaran adalah proses pengembangan diri. Markus 6:48, "Ketika Ia melihat betapa payahnya ... Lihat Selengkapnya
- MELANGKAH MAJU
- 22 April 2025
- Yohanes 19:38-40, "Sesudah itu Yusuf dari Arimatea --ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi-- meminta kepada Pilatus, supaya ia diperbolehkan menurunkan ... Lihat Selengkapnya
- PUNCAK PENDERITAAN
- 21 April 2025
- Kemarin telah kita pelajari tentang kasih serta mengampuni yang merupakan jalan setapak menuju kebahagiaan sejati. Yuk, sedikit lagi belajar soal mengampuni ini. Kita tahu teladan utama ... Lihat Selengkapnya